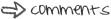Disinilah aku duduk. Sendiri, termenung, tertegun. Hujan pagi hari bentuk kabut tipis, selubungi dunia sekitarku. Bias-bias kaca kabur membentuk bayangan samar.
Ya, tepat saat seperti ini aku pertama kali bertemu dengannya. Dia datang menghampiriku.
“mengapa kau menangis?”, tanyanya.
Terheran, aku mendongakkan kepala, berusaha mengusir bingungku.
“tak mengapa aku menangis. Ini bukan urusanmu. Siapa kau?”, tanyaku.
Ia tersenyum manis, senyuman lebar membingkai wajahnya, damai laksana padang hijau.
“aku adalah potongan jiwamu, keping – keping yang tak kau sadari keberadaannya”, ujarnya.
“jangan menangis, air mata tak pantas telusuri wajahmu”, ujarnya seraya menghapus air mata dari pipiku.
Aneh, begitulah yang kurasakan. Siapakah dia, mengapa muncul begitu saja tak kusadari sebelumnya. Kutepis tangannya, namun digenggamnya tanganku. Hangat, pikirku, bagai kapas disinari mentari pagi. Hanya genggaman namun mampu usir sedihku bahkan kesedihan itu seolah tak pernah terasa ada.
“jangan takut, aku ada untukmu, biarkan angin sapu beban di pundakmu. Tidurlah, aku disini menjagamu”, ujarnya.
Kupejamkan mata. “harusnya kau datang sedari dulu, isi kekosongan hatiku”, bisikku.
Kulihat bibirnya membentuk senyuman. “tak masalah aku datang dari dahulu, kini atau mungkin di masa depan. Kau tak pernah tahu. Waktu adalah waktu. Ia pertemukan kita dengan caranya sendiri. Dan ia pulalah yang akan pisahkan kita. Aku milikmu saat ini”, ujarnya.
Kubuka mataku, kupandang ia, heran. “bagaimana kau tahu itu? Bila kau hendak tinggalkan ku, bila ini hanya ilusi mimpi, maka tak ada gunanya”, rengutku.
“tak perlu kau resahkan. Waktu tak bisa terulang. Dan kapankah gulirnya berhenti, tak ada yang tahu. Momen ini hanya milikmu seorang”, ujarnya.
Di sepanjang sisa pagi itu kami tak berbicara. Hanya duduk berdampingan. Kusandarkan kepalaku dibahunya, dielusnya rambutku. Surga kecil, oase yang lembutkan padang pasir. Kubekukan kenangan ini dalam kepalaku. Mungkin aku masih akan bertemu dengannya esok, mungkin pula tidak. Tapi aku tak ingin memikirkannya. Hanya menikmati pagi, bersamanya.
Sejak saat itu, kehadirannya isi duniaku. Tak pernah lagi ada masalah yang terlalu berat untuk kuhadapi. Bersamanya, aku dapat menertawakan segala kesukaran hidup. Ia selalu ada disekelilingku, membisikkan kata – kata penuh penghiburan tiap kali badai mulai menerpa. Ia juga yang selalu menyambutku dengan senyuman. Selalu ada tawa bersamanya. Selalu.
Ia menarikku bagai magnet berbeda kutub.
Aku kangen aji. Aku rindu dengan tawanya yang nyaring, lepas. Tangannya selalu siap sambut diriku, ketika aku akan melompat. Protektif sekaligus sensitif.
Beberapa hari menjelang keberangkatanku, kami mulai merasakan jurang membentang. Sedikit sekali yang dapat kuucapkan. Tangan kami lebih banyak berbicara. Bila tak ada orang di dekat kami, ia akan menggenggam tanganku. Lalu aku memandangnya, tersenyum. Meski sedih hatiku. Kupegang wajahnya, lalu ia tersenyum menatapku.
“ kamu kok mesti pergi sih jelek, aku mesti gimana kalo kamu ga ada. Ga ada orang bisa menghibur aku, ga ada orang yang begitu cerewet tapi aku tetap bisa tahan hadapi kamu”, ujarnya merengut. “jangan begitu mas aji, iwit ga pernah bener-bener pergi. Iwit selalu ada bersama mas aji, meski cuma jadi bayang – bayang”, ujarku.
Lalu kami kembali terdiam.
Hanya itu, momen bisu, tak perlu kata – kata untuk lukiskan perasaan kami. Kuhibur ia, berusaha ciptakan kenangan akan diriku. Teka teki lucu meskipun tak jarang membuatnya memutar bola mata selalu kulemparkan untuk mengisi kekosongan di antara kami. Dalam hati aku bertanya – tanya apa yang akan terjadi pada kisah kami berdua. Akankah ini akan berlanjut atau hanya berupa cerita singkat yang muncul sesekali dalam ingatan.
Hari – hari terakhir, ia mengajakku jalan – jalan. Tak perlu, ujarku. Tapi ia bersikeras. “Tak boleh, kamu harus memiliki kenangan akan bali. Akan diriku. Bila suatu saat nanti kamu datang mengunjungiku, akan kita ulang momen ini”. Dentang kesedihan kembali selimuti hatiku. Betapa tidak, pertemuan yang begitu singkat munculkan perasaan sayang dalam diriku. Kini, setelah kami memiliki kesatuan hati, kami harus dipisahkan jarak.
Kuturuti keinginannya. Sehari itu, kami berjalan – jalan berdua. Telusuri jalan yang panjang membentang seolah tak ada akhir. Ditunjukkannya tempat ia dulu pernah tinggal. Lalu kami berhenti di lovina. Kami berjalan berdampingan. Selalu tangannya menggenggam tanganku. Bila aku berusaha melepasnya, ia pasti menarikku kembali. Aku tertawa melihat tingkah lakunya. Begitu kekanakkan sekaligus manis.
Bila aku bersikap manja, ia akan mengelus kepalaku. Lalu disentuhnya pipiku.
“Kamu kok ya pendek banget ya jelek, kecil banget gitu,” ujarnya. Lalu aku merengut, berjalan menjauh darinya.
“duh, kok ya gitu aja ngambek, kamu ini hobinya ngambek ya”, ujarnya lagi.
“mas aji sih…”, ujarku, sebal dengan kata – katanya.
Kembali ditariknya aku seolah kami takkan bisa dipisahkan apapun jua.
Lalu hari itupun tiba jua, sehari sebelum keberangkatanku. Kami kembali bertemu. Kali ini ia benar – benar jadi pendiam. Apapun yang kukatakan tak banyak membuatnya tersenyum. Sebaliknya ia cemberut menatapku.
“besok kamu pergi, hari – hariku jadi kosong lagi”, ujarnya.
Aku hanya diam, tak mampu berujar apa – apa. Berat hatiku meninggalkannya. Kutempelkan kepalaku dipundaknya. Detak jantungnya berpilin dengan detak jantungku. Debaran yang kencang. Tersenyum, meski sedih kurasakan saat itu. Aku takut kehilangannya, kehilangan senyumannya.
Di bandara Ngurah Rai, aku pun mengucapkan salam perpisahan pada Bali. Aji tak bisa mengantarku saat itu karena ia masih harus bekerja, tetapi pesan singkat yang dikirimkannya temani perjalananku. Pesawat yang kutumpangi pun lepas landas, dari kejauhan aku dapat melihat Gilimanuk. Desa kecil yang pesonanya telah mengikatku. Disana pula aku sempat menjalin kisah asmara.
Hari-hariku berlanjut di Depok. Kembali berkutat dengan kuliah, dengan tugas akhir yang senantiasa melahapku. Hingga suatu ketika aku jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit guna menjalani operasi pengangkatan usus buntuku yang pecah. Aji selalu menemani, meski ia tidak ada disampingku. Ia meneleponku setiap hari, mengirimkan ratusan pesan singkat untuk menghiburku. Sungguh aku beruntung dapat merasakan perhatian dari seseorang yang nun jauh disana.
Ketika periode sakit itu usai, aku kembali menghadapi kuliah dan menjalani sidang. Syukur pada Allah aku berhasil lulus dengan gemilang. Aku segera menelepon Aji. Tapi ia tidak mengangkatnya. Kurasakan komunikasi kami mulai membeku tidak sehangat dulu. Beberapa saat kemudian ganti ia yang menghubungiku, tapi aku tak tahu sehingga aku tidak mengangkat teleponnya karena saat itu aku sedang merayakan kelulusanku bersama teman-temanku. Ternyata itu adalah komunikasi terakhir kami berdua. Setelahnya aku tak dapat menghubunginya. Tapi aku tidak mengeluh. Aku memahami resiko ini dari awal. Kami memang saling melepaskan. Ada tantangan yang kurasa tak akan bisa kami taklukan maka disinilah kami berada, di jurang perpisahan. Tak apa, pikirku, aku tetap menyayanginya, meski hanya sampai disitu kisahku.
+ + + + + +
Dua tahun berlalu sudah. Dalam kunjunganku beberapa saat lalu aku kembali bertemu dengan Aji. Salah satu temannya memanggilnya keluar dari kosnya. Kami pun bertemu, aku tersenyum sambil menyapanya.
“Mas Aji…apa kabar?” ujarku.
Ia pun balik tersenyum padaku. Kurasakan saat itu jantungku berdebar-debar tak karuan, meski hanya untuk beberapa saat saja. Kami pun berbicara dan bercanda layaknya teman lama. Kurasakan perasaanku padanya telah berubah. Aku menyayanginya hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Aku menyayanginya seperti aku menyayangi abangku. Tak ada perasaan kecewa dalam diriku, mungkin karena waktu itu aku memang ikhlas melepas dan menerima kenyataan bahwa kami tak bisa bersatu. Tak apa. Aku tetap berbahagia dan ia pun tetap menyayangiku. Aku dan Aji, kami pernah punya kisah di masa lalu namun tak ada perasaan sedih menaungi kami dan kami dapat saling menggenggam persahabatan yang berisikan tawa dan bahagia.
 |
| creating unforgettable moments at lovina beach |